Malam itu, baru saja
sesuap nasi yang kumasukkan dalam mulut, bunyi Talempong berdering memperanjatkanku. Memang musik Talempong itu kutetapkan sebagai nada
pesan Selulerku. Aku berusaha
meraihnya yang tergeletak di lantai samping dudukku.
“Hei, telepon dong.
Bosan!”, sebuah pesan singkat yang sangat kukenal orangnya. Dia orang paling
dekat, akhir-akhir ini selalu lengket menemani hari-hariku. Tanpa ba,bi,bu lagi
langsung aku pencet tombol menuju nomor yang sudah kukenal itu.
“Maaf, pulsa anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan, harap isi
ulang.” Sebuah suara protes operator itu membuatku kesal. Nampaknya operator
itu tahu betul rupa kondisi pulsa di Selulerku,
tanpa segan dia menyuruh mengisi pulsa pula.
“Hah, pantang! Tadi pagi
baru diisi sekarang minta diisi lagi, boros” desahku.
Aku langsung beranjak
menuruni anak tangga. Maklum saja, kamar kosku di lantai dua. Sebab kamar di
bawah terlalu berat biayanya untuk anak kost sepertiku ini. Gerimis sisa hujan waktu shalat Magrib malam itu aku lewati.
bawah terlalu berat biayanya untuk anak kost sepertiku ini. Gerimis sisa hujan waktu shalat Magrib malam itu aku lewati.
“Pulsa sepuluh ribu
Bang,” kataku pada tukang Counter. Hanya
anggukkan yang aku dapati. Entah ada apa, tukang Counter itu pendiam kini. Biasanya ketika aku menghampiri Counternya selalu ada senyum dan tanya
yang terlontar dari mulutnya. Tapi kini tidak. Aku tidak terlalu banyak
memikirkannya, dan langsung pulang tanpa berkata-kata.
“Hallo, maaf agak
lama”, sapaku.
“Ya, nggak apa-apa. Oh
ya, emang tadi ngapain?” balasnya datar.
“Pulsa habis, sekarang
baru pulang dari Counter,” jawabku
lagi.
“Oooo....”, begitu
bulat kudengar di ujung sana.
“Yo Mande..., antah jo apo ka denai baleh
Kami barampek kami mandeh gadangkan
Jo saba hati mande adokkan
Bareh
sagantang yo mandeh batanakkan
upah manuai manumbuk padi urang
.......................................................
Pambangkiak lukah salamoko nan tabanam
......................................................
Janjang patah pintulah rubuah, den himbau
mandeh indak babunyi.”
Putus-putus kudengar lagu
minang Ratu Sikumbang itu dilantunkan dari seberang. Menghembus, menderu relung
angin malam. Menelusuri gelombang pita suara sampai ke gendang telingaku. Aku
diam saja mendengar alunan nada itu. Lagu itu mengingatkanku pada kampung, Abah
dan Amak di seberang rantau. Di ujung pesisir.
Ya, aku tahu. Dia suka
sekali menyanyikannya, apalagi lagu-lagu minang yang menusuk relung hati. Lagu
ratapan, ngilu rasanya. Sedangkan aku hanya penikmat sejati, seakan tidak
pernah bosan mendengarnya. Aku juga tahu, meskipun suaranya tidak semerdu suara
Sulis penyanyi lagu islami, namun aku tetap terhibur dibuatnya. Entah apa
sebabnya. Bingung.
Uda...
japuiklah denai gunggunglah tabang
Bukannyo anggan denai menggunggung adiak
Dek badan indak badayo, bak cando ijuak
indak basaga
Uda...tabuihlah
janji jo mimpi-mimpi
U...sah turuikkan cinto di dalam hati
Bamain api adiak tabaka, bamain aie badan ko
basah
................................................................
Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba
saja jawabannya keluar dari mulutku. Tanpa dipaksa-paksa semuanya terlontar
begitu saja. Aku juga tambah tak mengerti. Mungkin karena lagu itu juga
termasuk dalam daftar kesukaanku. Terasa ibarat benar-benar sedang bernyanyi
dalam duet yang sesungguhnya. Bagai berdiri di rerumputan taman luas, saling
menjawab tanya di atas beranda rumah gadang, yang disaksikan beberapa kumbang
yang mencari madu diantara bunga. Lama kami mengulang-ulang lagu itu tanpa
lelah, tanpa bosan.
“Oh ya, besok jadikan kita ke Job Fair?” suaranya menghentikan
dangdutku. Ya, Dia seringkali mengatakan setiap aku bernyanyi selalu bernada
dangdut, padahal menurutku tidak.
Mantapku jawab “Jadilah”.
Kemudian melanjutkan bernyanyi lagi. Terdengar hujan pun semakin deras seperti
derasnya perbincangan kami malam itu. Dentuman titik hujan semakin kencang
keras menghujan bumi seakan tidak mau kalah dengan suara yang kami keluarkan.
Akhirnya cerita
mengalun begitu saja, seperti alunan gerimis hujan yang mulai reda. Perdebatan,
mungkin itu sebagai bumbunya malam biar tetap seperti siang, hidup. Kritikan
pun tak khayal juga datang padaku. Dia tiba-tiba dilepaskan dari busur mulut
yang selama ini menghiburku dengan lagu, tawa, bahagia. “Berarti dia peduli
denganku,” bisikku dalam hati.
Aku senang
mengenalnya. Baik, cantik, juga keras tapi lembut. Dia sosok wanita yang tegar.
Banyak pengetahuan hidup yang dapat aku cerna dari tuturannya yang tidak aku
punya. Dia jauh lebih dari teman-teman wanita yang pernah aku kenal. Di
hadapannya, terasa betul banyak kelemahanku sebagai lelaki dalam menjalani
hidup selama ini. Tak jarang aku harus memutar seribu kali otak dan hati
merenungkannya. “Kau wanita hebat” gumam hatiku tanpa menjauhkan ganggang seluler mendengar ocehannya. Sampai
menguap, lelap bersama mimpi.
***
“Lalok sakali....” sebuah pesan kubaca. “Astaga...ternyata tadi
malam aku terlelap”, kataku pada diriku sendiri. Kusibak jendela kos, kulihat
di atas ujung atap hitam dan kelam. Pagi yang berlangit mendung, tapi tidak di
hatiku. Tapi bagaimana....
“Sudah siap?” pesan
darinya memutuskan pembicaraan batinku pagi itu.
“Udah, kamu? Nunggu
dimana?” aku layangkan sebuah balasan. Bergegas aku mandi, menyisir rambut, dan
mengoles sisa-sisa parfum kesukaanku. Aku tarik tas, kukunci pintu. Kubuka
lagi, “dasar helm nggak bilang-bilang kalau ditinggalin,” gerutu hatiku.
Jawaban darinya belum
juga aku terima. Kulihat di layar seluler,
pesan tertunda. “Hah..sialan”, sambil kukirim ulang pesan
itu. Beberapa saat aku tinggalkan kos-an, terasa ada sesuatu yang bergetar di
celanaku. Aku raba-raba celana itu, tidak dapat, aku berhenti. Sebuah pesan,
“Aku sudah siap, aku tunggu di tempat biasa aja ya”.
Bagai ada yang membisikkan
sesuatu, terhipnotis, gas motor buatan Jepang kupelintir dengan kencang. Suasana
masih pagi, hanya beberapa orang saja yang terlihat berlalu-lalang. Ada juga
beberapa mobil, motor, yang menurutku banyak yang menuju ke tempat yang sama. Tidak
kupikirkan itu, bayanganku aku harus sampai dengan cepat. Ya, terasa sangat
mudah bagiku menerobos, memacu, mengejar garis-garis putih di tengah jalan.
Aku melihat sebuah
senyum sumringah mengambang dari kejauhan. Senyum kecil, namun bisa menggoncangkan
jantung, magnetnya berdampak besar mendebarkan dadaku. Semakin dekat, senyum
itu semakin indah. Aku yakin banyak yang tertegun memandangnya, itu dapat
kulihat dari ekor mataku pada wajah di jalan itu.
“Udah lama,” tanyaku.
“Nggak juga,” jawabnya
sambil menjangkau helm di tanganku. “Ayo,” lanjutnya sambil tangannya memukul
kecil di bahuku dan bergantung di sana. Roda motorku seakan-akan mengerti
tujuan, dia berputar mengikuti jari-jarinya, sesuai komando tanganku pada gas. Ya,
menuju acara mencari kerja, mencari uang.
Suasana yang asyik, karena
hari mendung. Di perjalanan banyak tanya disambut jawab yang terlontarkan. Sesuai
suasana hati yang cerah, secerah senyumnya yang terlihat dari kaca sapion, yang
sesekali aku melirik ke arahnya. Andai kata, aspal bisa berbicara, meskipun
sakit tergilas roda-roda jalanan, pasti ikut senang waktu itu.
Suasana masih terlihat
sepi, belum banyak yang datang. Hanya panitia yang terlihat sibuk mempersiapkan
segala sesuatunya. Tempat pengambilan tiket, dan ada beberapa orang yang
membagikan formulir juga. Beberapa pasang mata memandang ke arah kami. Aku
risih sekaligus bangga. Tahulah, aku mungkin tidak pantas membawa wanita
seperti Dia. Entahlah, aku memang jauh dari kata tampan, sedangkan Dia meskipun
berbalut dari produk biasa, tetap mempesona. Iya, Dia mampu menghipnotis hati
orang, dan aku juga orang itu.
Hufss... tidak ada
hasil hari itu, selain tiga lembar tiket. Kesalahan fatalku, ternyata aku diberikan
Tuhan sifat lupa, sehingga berkasku semuanya terbaring di atas komputer kamar
kos. Mungkin Dia kesal, namun tetap mengumbar senyum padaku. “Tidak apa-apa,
kita ulangi besok.” Hiburnya.
***
Malam itu seperti
malam-malam biasa. Malam yang mengingatkan kesalahanku siang itu. Kenapa sampai
lupa, kenapa harus..., pertanyaan kuajukan dan harus dijawab sendiri olehku
malam itu. Pesan di seluler sesekali datang
menghiburku, pesan dari Dia di ujung sana. Hingga membawa jiwa terlelap
panjang. Begitu juga ketika malam direnggut sinar mentari pagi. Rutinitas mulai
memanggil untuk dijamahkan setiap jengkal putaran waktu, tanpa lelah.
Aku dan dia langsung
mengendara waktu, menuju tempat memutar hidup, pelabuhan rutinitas berikutnya,
dunia kerja. Nasib memang tidak selalu beruntung, semua tawaran tidak sesuai
dengan yang ingin ditawar. Hanya satu dua saja tawaran yang mungkin bisa
menarik hatiku. Itupun belum pasti bakal diterima, “pokoknya dicoba aja dulu”,
bisiknya di telingaku.
Entah apa rencana Tuhan
siang itu. Suasana mulai kelam. Langit menangis sejadi-jadinya, bagai seseorang
yang kehilangan pujaan hati. Gelegar gemuruh menambah nuansa seram. Bumi terasa
tidak sanggup lagi menahan butiran hujan yang dijatuhkan. Sungguh Tuhan Maha
Tahu, sehingga tidak ada yang tahu maksudnya hari itu.
Mau tidak mau, suasana
itu juga memaksa kami untuk melawan arus hujan, bersuara keras agar pembicaraan
jelas. Aku dan Dia duduk berdekatan, bercerita, bersendagurau, memantapkan
rencana ke depan. Berharap kepada Tuhan semoga dimudahkan dapat kerja untuk
meraih sukses. Dia menceritakan adik-adiknya bakal melanjutkan pendidikan, karena
Dia tahu adik-adiknya punya kemauan juga kemampuan. Sampai jauh alur ceritanya,
tentang ibunya di kampung, ayahnya yang berdagang di rantau orang. Aku hanya
jadi pendengar setia, sesekali memberi penguatan dengan meng-Amin-kannya,
semoga do’anya dikabulkan.
Angin kembali
berhembus menusuk tulang-belulang, mengikuti irama deru hujan. Hawa dingin
begitu sangat terasa. Tetes demi tetes air menjatuhkan dirinya ke bumi, hingga
hanya tersisa bernama gerimis.
“Kita cabut aja yuk?”
suara di sampingku melawan sisa hujan itu.
“Gerimis, emangnya
nggak apa-apa?” sambutku. Dia hanya menggeleng lembut pasti. Aku mengiyakan
saja tanda setuju yang diberikannya. Berdua kami melewati gerimis dengan
berani, menjauh dari beberapa pasang mata di sekitarnya. Aku diam saja, fokus
memandang di sela-sela tetesan hujan yang mulai menyerang lagi. Dia di
belakangku mulai gelisah.
“Terawangan, aiiisssh....malu,”
katanya sambil tertawa di telingaku.
“Apanya terawangan?”
tanyaku datar sambil menoleh ke belakang. Akhirnya aku mengerti yang
dimaksudkannya. Aku kasihan. Aku menawarkan jasa untuk memakai jaket,
mengulurkan jaket hitamku. Dia menolaknya, mungkin Dia tahu aku lebih
membutuhkannya, sebaliknya aku tahu kalau Dia juga lebih membutuhkannya.
Hujan terasa
menghantam begitu kencangnya, angin terasa menembus ke seluruh persendian dan
aliran darah.
“Kita cari mantel
untuk kamu ya?” aku menawarkan lagi. Jawabannya tetap masih kata yang sama. Tawaranku
ditolak kembali. Aku diam. Dalam hatiku selalu mencari dan bertanya untuk
menolongnya dari hantaman hujan dan mata telanjang yang memandangnya. Aku tak
rela. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika mendengar jawabannya. Menolak
dengan keras kepala. Aku tidak bisa memaksa.
“Aku lapar, kamu?”
katanya.
“Sama.” Jawabku
sekenanya. Dalam keadaan basah, kami berdua menuju ke tempat makan yang sungguh
sederhana. Tempat makan yang hanya dinaungi oleh terpal. Meja-meja dan kursinya
basah. Terlihat pelayan membersihkannya ketika melihat kami memesan menunya. Pecel
Ayam dua, tempe dan tahu empat, dan segelas teh panas. Kesederhanaan terasa
begitu nikmat, suasana dingin dihidang dengan makanan yang hangat. Kulihat Dia yang
berada di depanku, wajah putihnya mulai pucat, pasti karena kedinginan.
Setelah siap, sekitar
jam 08.00 kami meninggalkan tempat makan yang sederhana itu. Ah, baru keluar
dari tempat itu saja, banjir sudah menghadang, depan belakang sama saja
dalamnya. Akhirnya aku memutuskan
memilih jalur kana. Astaga..., ternyata jalur pilihanku banjirnya lebih gawat
lagi. Lanjut, tanggung katanya.
Mmmbiurrrr...., sebuah
mobil dengan kencangnya berselisihan dengan kami. “Kurang hajar,” pekikku
serta-merta. Gelombang yang diciptakan mobil itu membenam motorku, mati
seketika. Semua pakaian kami sudah basah semua. Aku begitu geram pada pengendara
mobil,”mentang-mentang bawa mobil,” keluhku kesal. Kulihat Dia di belakangku
dari tadi hanya tertawa, seakan-akan sangat menikmati suasana itu. Hah...Dia
juga sangat menikmatinya, tertawa renyah ketika aku mendorong motor ke tempat
yang lebih aman.
Belum berapa jauh
kawasan banjir itu kami tinggalkan, masalah baru datang lagi, macet total
beberapa kilo meter. Kulihat keadaan hanya disesaki oleh ratusan kendaraan. Hujan
masih tersisa gerimisnya. Kulirik Dia, biasa. Aku ikuti permainan hujan hari
itu, biar basah menyusahkan, biar dingin menyelimuti, malam terasa tegang, batinku
berkata “nikmati saja”, begitu juga Dia dengan tenangnya.
Perjalanan pulang itu,
aku nikmati dengan suasana berbeda. Tidak ada lagi perasaan lelah di dadaku. Gerimis
malam terasa begitu indah menyentuh tubuhku yang basah. Dingin begitu lembut
mengalun di relung raga. “Indahnya kebersamaan ini, menikmati suka, duka, dan
senyuman. Bersama Dia, ya..hanya Dia,” gumamku ketika tiba di halaman rumahnya.
Lalu cabut ke kosku.
Seluluerku bergetar. “Hahahahaaa..., lucu betul ya kisah kita hari
ini, menyenangkan,” kubaca sebuah pesan dari Dia malam itu.
“Ya, lucu sampai
mendorong segala,” kukirim pesan balasan. “Rasanya aku ingin mengulanginya
lagi, berulang kali, hanya kita...hanya bersamamu, ya..hanya dengan kamu saja. Aku
akan selalu memimpikan itu,” bisikku dalam hati. Mimpi.... Ya mimpi membawaku
malam itu tanpa jawaban. Terus...menunggu jawaban tentang hujan esok hari. Hujan
terus bernyanyi dengan tetesannya tentang kita. Mungkinkah terulang.
Karya: Wahyu Saputra
Cerpen ini pernah
dimuat di Media Harian Singgalang, 24 Februari 2013
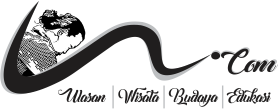






0 Comments
Jika bermanfaat tolong sebarkan dengan mencantumkan sumber yang jelas. Terima Kasih !